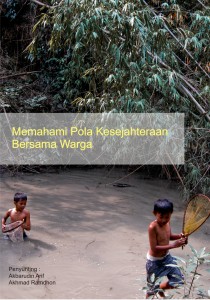Memahami Warga
Memahami Pola Kesejahteraan Bersama Warga
Penyunting, Akbarudin Arief-Akhmad Ramdhon
Penerbit Kompip Indonesia
Belajar (untuk) Berpihak
ebuah buku lama karangan Mahbub ul Haq (1982), menjadi pengingat kembali ketika harus menuliskan sebuah epilog bagi cacatan lapangan tentang persoalan kemiskinan. Sebuah buku yang memaparkan tentang realitas kehidupan masyarakat Dunia Ketiga, yang penuh dengan bekapan kemiskinan. Kemiskinan yang terdesain oleh sebuah kesadaran semu dan terbungkus oleh sebuah tatanan baru selepas Perang Dunia II berakhir. Sebuah kondisi yang general kemudian bisa kita lihat dampak kebijakannya lewat skema pembangunan yang dipaksakan di Asia, Afrika dan Amerika Latin hingga melahirkan mitologi pembangunan nan abai terhadap moralitas dan kemanusiaan.
Seakan-akan lupa dengan cacatan masa lampau tentang kesedihan manusia, Orde Pembangunan (developmentalism) tegak diatas upaya untuk mengabaikan fakta-fakta kemiskinan warganya, tegak kuasa diatas keterkungkungan dunia pers dan kukuh ditopang oleh militer sebagai eksekutor atas kebutuhan pelegallan tindakan Pemerintah. Negara yang semestinya bertanggung jawab atas kebutuhan warga kemudian menjadi pihak yang pertama kali mengkreasi kemiskinan menjadi sebuah situasi kolektif. Dengan menempatkan beragam indikator pertumbuhan pembangunan sebagai motor perubahan, semua instrumen negara menjadi pelaku terdepan untuk membungkam teriakan penderitaan yang terlalu banyak dan menggantikannya dengan angka-angka stabilitas gerak pembangunan.
Pembangunan kemudian bertransformasi menjadi ide yang mengisi setiap benak warga bangsa, tanpa kecuali. Jargon kolektif bangsa ini serta merta menempatkan kata kemajuan linear dengan pembangunan sekaligus mengalahkan cerita-cerita kecil tentang kemiskinan, menenggelamkan kabar ketidakadilan. Kabar kemajuan didengung-dengungkan disetiap ruang-ruang pengap pendidikan yang jauh dari semangat kritis, disebar dalam pamflet-pamflet yang diusung aparat dalam ritualitas birokrasi dan mengabarkan semua kebaikan yang akan tercapai oleh bangsa ini kepada anak-anak kita agar mereka bangga tentang bangsa yang sedang membangun ini (Kenichi Ohmae, 1995).
Pembangunan menjadi idiom yang senantiasa kita dengar bersama upaya untuk menegakkan kekuasaan yang menuntut loyalitas warga. Namun selalu ada permasalahan tiap kata pembangunan itu didengungkan oleh negara/kekuasaan yaitu relativitas makna pembangunan itu sendiri. Dari kondisi yang relatif, pembangunan sering kali mengalami distorsi pemaknaan-yang seharusnya terkandung didalamnya. Di sinilah Peter L Berger (1982) meletakkan titik tolaknya untuk melakukan kritik terhadap berbagai upaya pembangunan. Berger menuntut adanya etika yang baku ketika kita berbicara pembangunan dan standart dari etika itu adalah moralitas. Berger melihat, di negara-negara yang mengadopsi pembangunan, semua diwajibkan mengadopsi akan kemajuan, pertumbuhan, peningkatan, diferensial kelembagaan hingga pemerataan pembangunan (H.W. Arndt, 1998 : Sritua Arief dan Adi Sasono, 1984). Dan kesemuanya telah menjadi bius untuk kita semua yang kemudian selalu dituntut merasionalisasikannya.
Upaya untuk selalu merasionalisasi berbagai slogan pembangunan, menjadi blunder yang akan berimplikasi pada mitologisasi sekaligus pengsakralan tiap-tiap instrumentasi pada penegakkan kekuasaan. Berbagai mitos tersebut kemudian dilanggengkan oleh kekuasaan untuk selalu memperbaharui dan mengkonsolidasi kekuasaan. Berbagai propaganda akan pembangunan didengungkan seiring dengan tuntutan akan loyalitas dalam bentuk pengorbanan rakyat atas sebuah nama pembangunan. Yang terjadi sesudahnya adalah berbagai penindasan atas nama kemajuan, penghilangan atas hak-hak individu atas nama kolektifitas hingga pelanggaran pada rakyat atas nama penegakkan kepentingan negara. Dengan gerbong pembangunan, negara melakukan berbagai kejahatan terhadap rakyat dengan instrumen kekuasaan ataupun bentuk-bentuk lain dari antagonisme politik kekuasaan. Dan penting juga untuk ditulis, para kaum intelektual juga menjadi bagian dari penegassan kekuasaan. Dan itu semua terjadi pada setiap kata-kata pembangunan terdengar dimanapun atas dasar ideologi apapun.
Cita-cita pembangunan harus berakhir dengan sebuah realitas utopis, ketika pembangunan mengalami mitos untuk kemudian menjadi sebuah kehampaan karena berbagai penerapan sistem otoriter yang tidak memberikan ruang bagi hak-hak warga. Pembangunan telah mengambil pengorbanan yang amat banyak, biaya kemanusiaan yang harus ditebus oleh beberapa generasi, dampak psikologis dari tiap anak bangsa yang selalu trauma pada penderitaan orang tua mereka menjadi sebuah harga yang amat mahal yang harus kita tanggung atas transaksi kepentingan yang berslogankan pembangunan. Berger mengalami sendiri berbagai kontradiksi realitas akibat penegakkan kekuasaan dengan corong pembangunan.
Wacana kritik tentang pembangunan tentu tidak pernah absen, sebagai upaya menggugah kesadaran kita sebagai bangsa untuk mau belajar dan berubah. Kritik hadir untuk memberi penegasan bahwa pembangunan yang mengabaikan kolektifitas kebutuhan warganya hanya akan menjadikan narasi bangsa sebagai bangsa yang bangga oleh kisah-kisah nan indah yang dipaksakan diruang-ruang ideologi oleh negara. Namun kesadaran tentang efek gelap pembangunan tak kunjung hadir sekaligus menjadi mekanisme evaluasi atas berjalannya roda pembangunan selama tiga dekade.
Butuh krisis yang teramat besar untuk memalingkan kejumudan negeri ini atas pilihan kebijakannya yang penuh resiko. Krisislah yang membuat kesadaran baru akan keroposnya pondasi pembangunan oleh rezim Pembangunan setelah memasuki dekade tahapan pembangunan yang kelima. Bayangan akan tinggal landas kemudian tergantikan oleh situasi yang tak pernah terbanyangkan, dimana seluruh pondasi negeri terguncang oleh perubahan tak terperikan. Rezim harus tergantikan lewat pengorbanan anak-anak bangsa yang membela hak-hak mereka, disintegrasi serta merta menjadi sebuah wacana kolektif bangsa, konflik horisontal lahir dimana-mana atas beragam alasan.
Semua kebersamaan hidup yang dulu pernah ada kini berganti oleh ketakutan dan ketidak percayaan satu sama lain. Bangsa serta merta terseret oleh badai perubahan yang ada tanpa ada kemampuan untuk bertahan. Yang tersisa hari ini adalah penderitaan warga yang senantiasa terabaikan, bahkan selepas satu dekade kita mendeklarasikan Reformasi sebagai sebentuk jawaban untuk menganulir rezim Pembangunan yang telah tumbang oleh krisis.
Peter L Berger (1980) menjadi penting karena sengaja memantik diskursus bagi kotak pandora yang belum selesai hingga kini yaitu masalah keberpihakan seorang intelektual terhadap realitas yang ada. Keberpihakan yang akan menuntut standart nilai yang seharusnya berlaku bagi intelektual apakah mereka harus berada pada sebuah ruang yang lepas dari kebenaran realitas atau meletakkan sebuah standart nilai pada sebuah realitas yang hanya menawarkan berbagai subyektifitas kebenaran. Kerja-kerja pengetahuan sedianya tak boleh terperosok dalam perdebatan tersebut tapi langsung menentukan keperpihakannya atas realitas yang dihadapinya sekaligus menuntut keterlibatan sebagai bentuk tanggung jawab intelektualitas. Sebuah keberpihakan yang didasarkan atas moralitas yang universal (Philip Quarles-Ananta Kumar, 2003). Sekaligus mengetengahkan sebuah etika politik bagi para pengambil kebijakan, di tengah-tengah perubahan sosial yang dewasa ini sedang berlangsung di seluruh belahan bumi ini.
Inilah krisis ilmu pengetahuan yang berawal dari ketiadaan kritik empiris, dimana kebanyakan pemaknaan akan realita yang dimiliki oleh banyak ilmuwan sosial tak bermuara pada realitas yang ada dan situasi ini tak terpisahkan oleh sebab epistemologi ilmu yang digunakan yaitu pendekatan struktural yang menjadi maindstream bagi ilmu sosial di Indonesia (Ignas Kleden, 1984). Nalar tersebut berimplikasi pada lahirnya jarak antara kenyataan dan pengetahuan, hingga rapuhnya metode berpengetahuan yang sebenarnya menuntut pemaknaan yang serius bagi the body of knowledge dan kemudian mendapatkan pengetahuan berbasis pada kenyataan yang sesungguhnya.
Pengadaptasian pengetahuan yang terjadi hanyalah didedikasikan untuk membangun legitimasi kekuasaan politik negara atas warganya. Terjadi diskriminasi dalam sebuah proses pembelajaran yang ada, dimana akumulasi pemahaman yang mestinya beragam dalam pola pendekatannya terhadap realitas kemudian dimonopoli dan diekspansi. Keberpihakan yang ada hanyalah manipulasi dari sebuah upaya pelestarian akan kekuasaan yang menghabiskan tenaganya untuk mengembar-gemborkan pembangunan sebagai jalan satu-satunya (Ozay Mehmet, 1999).
Realitas kerja berpengetahuan yang seharusnya mengangkat nilai-nilai kemanusiaan kemudian tergantikan oleh penyeragaman pola pikir hingga ketakutan untuk berbeda. Perbedaan sebagai pondasi dasar dalam kehidupan kemudian harus dihilangkan dan konflik yang seharusnya ada, kemudian dipendam dalam-dalam. Kita tak pernah mengenal perbedaan dalam ruang-ruang kebudayaan yang ada, kita terkungkung oleh kebutuhan stabilitas sehingga regulasi kepentingan setiap orang sebagai bagian dari proses demokratisasi, tak terjadi. Sejarah masa lalu bangsa ini yang sangat dinamis (W.F. Wertheim, 1999) kemudian berganti dengan stabilitas masyarakat yang terciptakan oleh pengawasan aparatur negara. Penjelasan ilmu pengetahuan (sosial) terhadap realitaspun mengalami kegagapan sehingga kita kesulitan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi dalam masyarakat hari-hari ini. Oleh sebab telah berjaraknya ilmu sosial yang ada dengan kenyataan yang terus bergerak secara dinamis, beragam masalah yang menjadi beban bangsa ini, tak terselesaikan oleh kontribusi ilmuwan sosial.
Maka menjadi penting, ketika ilmu sosial mulai mengadaptasi berbagai hal berkaitan dengan penjelasan atas perubahan yang terjadi. Kesadaran akan kebutuhan memaknai demokrasi, memahami relitas masyarakat secara intens serta tak berjarak, membangun kesadaran serta memberdayakan masyarakat atau mengkritisi kebijakan negara atas ketidak berpihakkannya terhadap publik, menjadi sebuah kebutuhan yang tak terbendung seiring dengan laju perubahan global (James Lee Ray, 1998). Beragam penjelasan terhadap realitas yang baru akan menjadi sebuah dasar dalam merespon perubahan itu sendiri. Dan disitulah kemudian ilmu pengetahuan (sosial) menemukan ruang axiologynya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari realitas kehidupan masyarakat dan ilmuwan sosial menemukan eksistensinya sebagai cendikiawan (Kuntowijoyo, 1998).
Dalam rentang perubahan yang sangat deras, kerja-kerja pengetahuan mesti mampu membangun inisiasi warga agar berdaya bila berhadapan dengan negara yang senantiasa tak bersahabat. Masyarakat yang berdaya menjadi sebuah tujuan dari proses demokrastisasi dalam alam negara yang modern, dimana masyarakat sadar akan kebutuhannya, paham akan berbagai sebaran informasi dan mampu mengambil inisiatif dalam memperjuangkan hak-haknya (Christopher Pierson, 1996). Identitas warga yang mandiri (citizenship) terbangun oleh melebarnya ruang-ruang pengetahuan yang telah diinvestasikan oleh ilmuwan sosial. Keberdayaan warga akan berujung pada orientasi kebijakan negara yang memihak kebutuhan masyarakat secara luas dan disinilah bingkai dari peran ilmuwan sosial, menemukan kejelasannya.
Dengan pola pendekatan ekonomi-politik sebagai sebuah hipotesa, relasi antara negara dan warga dapat dikaji secara kritis sehingga beragam pola pendekatan keilmuwan yang ada, mesti jelas keberpihakkannya. Dengan pendekatan sosiologis yang menempatkan warga sebagai subyek maka kebutuhan secara metodologis untuk mengawali sebuah pendekatan yang berani berpihak dalam epistimologi pengetahuan harus segera dimulai. Problematika empiris yang menempatkan realitas masyarakat sebagai variabel yang terabaikan pada catatan masa lalu perkembangan ilmu sosial di Indonesia, mesti segera tergantikan (Samuel Haneman, 2012). Kedepan, yang harus terbangun adalah perwakilan kaum terdidik untuk belajar didalam proses kehidupan masyarakat, memahami, berdekatan, bersama-sama menikmati proses dan bersama-sama membangun kesadaran-partisipasi kognitif (Britha Mikkelsen, 1995). Sebuah kesadaran sebagai individu yang mempunyai seperangkat hak dan kewajiban, dalam relasinya dengan warga negara yang lain, dalam bingkai masyarakat yang demokratik.
Hadirnya kesadaran dalam bentuk partisipasi kognitif memungkinkan pada tiap proses kebijakkan politik, sekaligus kebebasan individu untuk mendefinisikan berbagai situasi yang mereka hadapi dan pemberdayaan lembaga-lembaga kemasyarakatan sebagai struktur perantara bagi warga dengan warga yang lain atau individu dengan kekuasaan sekaligus membangun kemampuan individu untuk merasakan makna-makna pembangunan yang semestinya. Karena itulah negara ditegakkan atas asumsi adanya kesepakatan kolektif dari individu, dimana individu kemudian menyerahkan kepercayaannya pada negara dan tidak ada yang lebih berhak mengajukan hak-kewajiban atas negara kecuali individu sebagai warga negara.